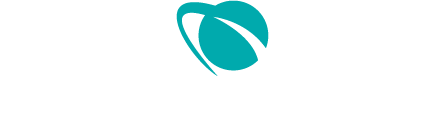Pengembangan Infokom (ICT - Information and Communication Technology) Indonesia masih mengalami banyak kendala. Policy Framework-nya masih belum jelas, Indonesia mau unggul di aspek apa - hardware, software atau kedua-duanya? Akibatnya, masing-masing entitas mengembangkan visi infokomnya sendiri-sendiri, sehingga tumpang tindih.
eBizzAsia: Bagaimana visi Telkom dalam pengembangan infokom?
Kristiono: Kalau bicara visi infokom, mestinya tidak bisa melihat Telkom sebagai satu business entity, sebagai satu pemain saja, tetapi justru harus berangkat dari konteks makro. Kalau bicara dari macro level, seharusnya industri ini di-setting sebagai apa, supaya paling tidak memberikan nilai tambah maksimum pada negara. Juga para pemain yang ada dalam industri ini, supaya mereka survive.
Sebenarnya, industri ini di-setting seperti apa? Mestinya kita harus banyak belajar bagaimana negara-negara lain melakukan itu. Kalau bicara industri TI, apalagi infokom, sebenarnya sekarang ini kan ceritanya cerita buruk, karena industrinya colapse, baik di wireless, wireline, industri equipment maupun media. Saya rasa hampir dalam tahun 2001 saja kapitalisasi pasarnya loss sampai 7,2 triliun dolar. Saya kira yang paling dramatis ada sekitar top 20 yang bangkrut, seperti WorldCom, GlobalCrossing, Level Three, dsb. Tidak hanya masalah bagaimana mereka melakukan itu, persoalannya ada skandal keuangan juga.
Kalau dilihat kecenderungannya, di wireless, Eropa colapse umumnya karena lisensi 3G. Sementara market-nya tidak ada. Kalau di wireline, Amerika colapse, karena masalahnya mereka sangat optimis. Intinya ada tiga, satu karena terlalu optimis, maka mereka excessive di capacity, akhirnya excessive juga di leverage. Contohnya Amerika, bagaimana mereka bermimpi industri internet akan tumbuh luar biasa. Akibatnya, semua pemain membangun jaringan data yang luar biasa. Asumsinya akan terjadi konvergensi, jaringan voice menggunakan jaringan data. Investasi di fibre optic juga luar biasa. Ternyata traffic internet dan data tidak sebesar itu, akibatnya bangkrut semua. Capex-nya begitu besar, revenue-nya tidak muncul, traffic-nya tidak cukup. Karena over optimist, akibatnya over capacity, kemudian over leverage. Jadi debt equity-nya sama sekali tidak “nyambung” dengan cash flow-nya. Kalau wireline di Amerika, sedang wireless di Eropa.
Semua dulu berpikir bahwa everything becoming online, semua akan menjadi e-Business. Seolah-olah infrastruktur itu jalan, kemudian tiba-tiba secara overnight menjadi online. Nyatanya tidak. Traffic juga tidak ada. Jadi, yang digembar-gemborkan itu jauh dari realita. Akibatnya kebangkrutan di media, dotcom, dan lainnya.
Tentunya tidak sama di semua negara?
Kalau dilihat peta per negara, memang agak beda. Itu penting bagi kita untuk belajar agar jangan sampai mengulangi jebakan-jebakan yang sama. Misalnya Amerika, sekarang yang survive itu yang punya customer dan itu di wireline.
Wireline internet mereka sudah sangat murah. Cuma wireline operators itu under pressure dari cables. Kenapa cables jadi threat baru, karena cables itu dulu dipakai untuk pay TV, terus kemudian dipakai untuk high speed internet pada cables yang sama. Tapi sekarang justru muncul triple bundle, dimana VoIP (Voice over Internet Protocol) sekarang termasuk di situ. Itu, jadi ancaman baru di Amerika. Jadi wireline operator, seperti Telkom, kena ancaman dari cable data. Sedangkan di wireless, growth-nya tidak terlalu bagus karena standarisasinya tidak seragam. Sebaliknya, di Eropa, wireline yang lebih superior, karena cable belum terlalu besar, dan wireless mereka kena masalah dengan 3G.
Lain lagi dengan Jepang, mereka sukses di bisnis data dan wireless. Bisnis model yang paling baik itu Jepang dengan NTT DoCoMo-nya. DoCoMo punya 40.000 websites karena business model-nya very simple, dimana dia hanya menguasai 5 persen, sedangkan 95 persennya dibagi ke content provider. Selain itu, mengapa internet cellular tinggi, karena – meskipun penetrasinya tinggi - wireline internetnya masih mahal.
Cina, peran policy government dalam pembangunan infrastruktur itu luar biasa. Jadi driver-nya bukan private, tetapi government. Dalam transfer teknologi, pemerintah punya policy membangun industri lokal. Karena market-nya besar, semua vendor masuk - meskipun marjinnya kecil - tapi dia harus menyerahkan teknologinya.
Selain peran pemerintah, siapa pemain utamanya?
Pemerintah hanya sebagai regulator dan policy maker saja. Pemainnya sebagian state owned companies yang kecenderungannya akan diprivatisasi juga. Bagusnya Cina punya kebijakan infrastrukur itu nomor satu. Yang kedua, semua vendor harus menyerahkan teknologinya untuk memperkuat industri lokal. Makanya semua industri lokal di sana scaling up-nya cepat sekali, karena teknologinya harus diserahkan. Jadi dalam 3-4 tahun set up industrinya cepat dan grasp market-nya juga cepat. Semua teknologinya di-copy habis. Kalau melihat switching-nya Huawei misalnya, itu tidak bisa dibedakan dengan buatan Lucent. Router-nya, tidak bisa dibedakan dengan Cisco.
Apakah di Korea juga relatif sama pola pengembangannya?
Korea, driver awalnya adalah internet café atau warnet. Di warnet itu selain akses internet, ada gaming-nya, dan juga e-learning. Itu menjadi bagian media yang mengedukasi. Di sana penetrasi internet itu bagus sekali dan aksesnya juga murah, bahkan dulu kalau perlu disubsidi. Setelah penetrasinya tinggi, baru dikompetisikan, jadi sekarang tidak boleh disubsidi lagi.
Dari typical banyak negara, kita bisa belajar bahwa Indonesia itu resources-nya tidak banyak, jadi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Basis industrinya memang tidak ada, yang ada hanya trading. Local access di kita itu bukannya mahal, tapi karena akses internet di-blending dengan local access, akhirnya jadi mahal. Sebenarnya tarif lokal kita ini masih disubsidi 30 persen. Sedangkan sekarang, orang ke ISP masih harus bayar local access plus service. Seharusnya tidak begitu, ISP dengan Telkom mem-bundling-nya, sehingga pelanggan dibebani untuk satu paket saja. Mungkin kita bisa belajar dari Korea dengan internet café sebagai suatu community access. Di sini penetrasi PC masih rendah, serta individual access masih mahal, jadi mungkin community access-nya yang harus ditinggikan.
Bisakah hal itu dijembatani Telkom?
Bisa. Mereka bisa diasumsikan sebagai reseller, bukan retail customer. Justru ini yang penetrasinya harus tinggi, sebagai learning media, dimana orang yang tidak punya PC bisa belajar.
Dari Jepang kita bisa belajar bahwa perlu adanya business model, supaya industri content itu tumbuh. Industri content itu tumbuh bilamana “pipanya” tidak banyak, sehingga lebih efisien dan bisa memberi benefit kepada industri content. Colapse-nya di Amerika itu karena overcapacity. Karena Indonesia resources-nya tidak banyak, kita harus berpikir efisien. Contohnya backbone. Persoalan backbone itu sebenarnya tidak hanya Telkom. Telkom punya, Indosat mau buat, Excelcom punya, PN Gas punya, PLN punya. Kenapa sekarang masing-masing berpikir menjadi pemain sendiri-sendiri? Kenapa tidak disatukan? Karena invest sendiri-sendiri akan terjadi duplikasi, padahal sumber daya kita terbatas. Backbone itu investasinya sangat tinggi, jangka panjang dan risikonya juga tinggi.
Berarti ada duplikasi lokasi, dong?
Ya, lokasi. Sekarang coba lihat Jawa, Indosat punya, Telkom punya, Excelcomindo punya, Gas punya fibre optic, PLN punya. Terus semua berlomba-lomba investasi, untuk apa? Kalau ini disinergikan, backbonenya satu saja, kemudian sumber daya yang ada bisa diinvestasikan untuk penetrasi di akses. Sekarang PLN punya PLC, Telkom juga investasi, Indosat juga , di seluler juga banyak.
Apa alasan utamanya?
Ya, karena tidak ada central policy. Ini kan keangkuhan sektoral. Contohnya, kenapa sekarang operator selular membangun tower sendiri-sendiri. Kenapa tidak belajar dari Eropa? Setelah bangkrut, mereka melakukan outsourcing total. Jadi mereka melakukan cost restructuring dengan cara outsourcing. Sampai 2010, enam puluh persen cost adalah untuk outsourcing. Dengan outsourcing benefit cost savingnya, kira-kira 10 persen . Optimum kira-kira 30 persen.
Ada suatu perusahaan di Eropa yang ketika bangkrut memiliki sekitar 14.000 tower. Setelah bangkrut, mereka melakukan restrukturisasi dengan meng-outsource operasionalnya. Jadi tower-tower seluruhnya di-outsource, bahkan sampai operasi core competence-nya juga di-outsource ke para vendor. Lalu kenapa di Indonesia semua masih membuat tower sendiri. Kenapa tidak di-outsource saja? Jadi ada satu atau beberapa perusahaan yang menyediakan tower, yang bisa dipakai bersama. Dengan begitu cellular operators bisa saving investment berapa besar. Bayangkan, membangun satu tower itu bisa 500 juta. Misalnya, Telkomsel, ada sekitar 3.000 sites, dikali 500 juta sudah berapa? Belum lagi Satelindo, IM3, Excelcomindo. Memangnya mau balapan tower. Kalau satu tower digunakan bersama, tentu lebih efisien.
Maksud saya, apakah Indonesia harus menunggu colapse dulu baru berpikir ke situ? Eropa sudah jelas, Amerika juga, bahkan yang diuntungkan kan Asia, baik di wireline maupun di wireless. Asia yang kapitalisasinya paling bagus atau stabil. Karena apa? Karena Asia tidak terlalu over exposure.
Infrastruktur itu sangat penting?
Ya, jadi kalau orang bicara I before e, I (infrastructure) itulah yang investasinya paling besar. Itulah yang harus dihemat betul. Bagaimana caranya semua potensi itu disinergikan untuk mendapatkan infrastruktur yang kapasitasnya besar, merata dan mempunyai akses kemana-mana. Karena kalau pipanya semakin luas, kapasitasnya semakin besar, ini menjadi kunci bagaimana industri ikutannya jalan. Bagaimana memberikan akses yang lebih murah karena investment-nya efisien, dengan lebih murah traffic akan digenerasi, kemudian industri content dan lain-lain akan ikut tumbuh.•