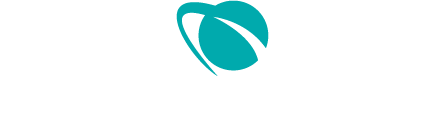Budi Wahyu Jati, Country Manager Intel Indonesia Corp., langsung menunjuk ketidakbiasaan untuk mendokumentasi sebagai salah satu kendala bagi kebanyakan pengembang software lokal. “Saya sudah terlalu sering mendengar cerita itu,” katanya. Ia mempertanyakan bagaimana bisa terjadi membuat software tanpa ada dokumentasinya. Hal itu terasa ketika software itu bermasalah atau saat hendak di-upgrade, karena tidak adanya dokumentasinya maka mau tidak kembali dari awal lagi.
Di matanya, software tanpa dokumentasi sangat tidak logis. Karena ketika piranti tersebut diserahkan maka sulit untuk bisa membaca bagaimana arsitektur dan strukturnya secara rinci. Belum lagi untuk keperluan pengembangan aplikasi yang baru sebagai tambahan terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Celakanya, hampir sebagian besar pengembang lokal justru melakukan itu. Hanya sedikit pengembang lokal yang sudah memiliki kedisiplinan untuk mendokumentasikan secara rinci dan jelas.
Tidak heran bila Andrari menyebut ketidak-terdokumentasian itu sebagai kebiasaan para tukang. “Tukang tidak perlu dokumentasi,” katanya. Tapi, itu tidak otomatis menjadi kesalahan para pengembang lokal. Menurutnya, end-user sangat tidak peduli terhadap dokumentasi. Kalau pun dokumentasi tersedia, end-user tidak berkeinginan mengujinya. End-user dan pengembang lokal sama-sama puas ketika sistem itu running well saat pengujian.
Ketidakdisiplinan terhadap dokumentasi, sebenarnya merugikan pengembang itu sendiri. Pengembang justru kelabakan saat programmer bersangkutan hengkang. Pasalnya, source code-nya pun ikut hengkang bersama sang programmer. Persoalan lain, tidak ada yang bisa dilakukan perusahaan pengembang jika kliennya membutuhkan pengembangan atau upgrade software yang mereka pesan.
Markus juga tidak menutup mata atas fenomena yang terjadi, namun ia tidak ingin menyamaratakan. Di matanya, ia melihat bahwa sebagian pengembang lokal justru sudah mengikuti kaidah-kaidah industri dan perekayasaan industri software. Karena itu dokumentasi yang dibuat harus bisa mencatat semua perencanaan dan eksekusi, mulai dari tahap awal hingga sebelum diserahkan ke pelanggan.
Ia juga tidak menutup mata ada pengembang lokal yang melakukan taktik ‘quick and dirty’. Selain tidak terdokumentasi juga sebenarnya pengembang semacam itu tidak peduli, apakah setelah uji coba produknya masih bisa perform secara optimal. “Mereka juga tidak ambil pusing apakah nantinya bisa dimigrasikan, dimodifikasi atau di-upgrade”, katanya. Pengembang lokal harus mulai memikirkan bagaimana kemungkinan migrasi atau perubahan tanpa harus mengorbankan data-data dalam database sebuah perusahaan. “Kalau database-nya masih kosong tidak jadi persoalan, tapi kalau itu sudah dimiliki bertahun-tahun ‘kan jadi masalah besar,” lanjutnya.
Itu sebabnya Budi melihat bahwa end-user manapun tidak mau menjadi korban dari kebiasaan buruk semacam itu. End-user yang mengerti TI tidak berkeinginan untuk menjadi kelinci percobaan hanya karena harganya murah. Tidak heran bila sebagian besar end-user cenderung memilih standard atau package software yang sudah terbukti kehandalannya.
Tidak heran bila kemudian membiasakan pendokumentasian sebagai kebiasaan rutin menjadi pilihan untuk mengubah tabiat pengembang lokal. Marsudi merujuk perolehan sertifikat ISO yang menekankan pentingnya ketertiban termasuk soal pendokumentasian. “Tertib berdampak tidak langsung pada peningkatan kualitas,” katanya.
Yang paling penting adalah merubah paradigma yang melekat di benak pengembang lokal, dari rumah software menjadi industri software. Jelas bahwa itu berarti perubahan mindset secara besar-besaran. Berarti juga pengembang lokal sudah harus berpikir untuk menjadikan bisnisnya sebagai bisnis yang berkesinambungan. Tidak sibuk dengan proyek sekali pukul yang selama ini menjadi gantungan hidupnya.
Pengembang lokal tidak lagi membatasi dirinya dalam skala pengembangan. Ini, menurut Bobby, justru memungkin para perekayasanya bisa menambah terus jam terbangnya. Penambahan jam terbang juga mengharuskan para perusahaan pengembang lokal sudah memikirkan kemungkinan penciptaan jalur karir tersendiri bagi para perekayasa. “Di sini kalau jadi manajer malah repot dengan urusan manajemen dan administratif,” tambah Bobby.
Di balik semua itu, permasalahan yang pelik justru terdapat dalam sumber daya manusia TI. Menurut Marsudi, dari 175.000 lulusan informatika hanya 2% yang bekerja di bidangnya. Sedemikian kecilnya jumlah tersebut, bukan hanya persoalan persaingan dalam rekrutmen dengan lulusan teknik elektro dan matematika. Tapi juga masalah ketereksposan ke pasar lokal, seperti yang dilontarkan Bobby. Menurut Bobby, pendidikan tinggi informatika masih baru di sini. Di samping itu pasar yang berkembang masih sangat terbatas, terutama untuk perekayasa software.
Untuk perekayasa, Bobby melihat masih diperlukan berbagai pengkayaan yang sebenarnya tidak bisa diperoleh di bangku kuliah. Itu justru diperoleh ketika bekerja dalam lingkungan kerja yang sistematis. “Kemampuan beradaptasi kita dalam menata diri untuk bekerja secara sistematis memerlukan waktu relatif lebih lama,” jelasnya. Di samping itu, para lulusan juga kesulitan mencari role model dalam proses pembelajaran untuk membuat program yang baik dan memenuhi skala perekayasaan yang sangat ketat.
Bobby menunjuk dunia pendidikan India, yang memberikan kesempatan pengkayaan ketrampilan bagi para mahasiswanya sebelum lulus. Hal itu sangat kritikal dan bisa dipersamakan dengan pendidikan yang diperoleh oleh para mahasiwa kedokteran di sini. “Di sini orang tidak mengeluh soal pelayanan kedokteran karena pendidikan kedokteran memiliki waktu yang lebih panjang dan itu diperlukan untuk memperkaya ketrampilan,” katanya.
Bagi Marsudi sebenarnya pemenuhan SDM TI yang memadai kemampuan dan ketrampilannya seharusnya bisa diselesaikan pendidikan formal. Menurut Marsudi, masih banyak pendidikan TI yang mengajarkan mata kuliah yang sebenarnya sudah usang, seperti pengajaran mengenai operating system. Sekalipun telah diberlakukan liberalisasi pendidikan nasional, namun yang terjadi adalah tidak banyak lembaga pendidikan yang mampu memanfaatkannya. Ia melihat bahwa kurikulum nasional 5 tahun lalu masih saja digunakan di banyak perguruan tinggi informatika. Sehingga, tidak banyak perguruan tinggi yang mampu menelurkan kurikulum yang mengikuti kaidah-kaidah dan mendukung program industrialisasi software di Indonesia.
Lambannya perubahan itu ditambah dengan miskinnya praktik-praktik pendukung yang memungkinkan pengkayaan ketrampilan mendorong Marsudi mengkuatirkan lebih banyak sastra informatika daripada teknik informatika sesungguhnya. Maksudnya, mahasiswa lebih banyak mempelajari dari buku-buku teks, daripada melakukan kerja praktik yang benar-benar riil.
Kondisi semacam itu ternyata juga menumbuhkan peluang bermunculannya sejumlah pendidikan nonformal informatika. Namun menurut Bobby, baru beberapa tahun terakhir ini, pendidikan nonformal yang beraliansi pada produsen-produsen software internasional hadir di sini. Pendidikan semacam ini justru menjadi pengisi kekosongan karena memang diperlukan dalam proses pengkayaan dan peningkatan ketrampilannya. Sejumlah perguruan tinggi informatika ternama bahkan telah menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga serupa untuk bisa membekali mahasiswa agar lebih komprehensif.
Di UI, menurut Bobby, hal tersebut masih diletakkan di akhir masa pendidikan. “Jadi bagian kurikulum yang sering diutak-atik adalah bagian ujungnya ini, namun kami masih menekankan pada pendidikan dasar dan menengah agar menjadi landasan yang kuat,” jelasnya. Sebab, kombinasi yang seimbang adalah pendidikan dasar yang kuat, skill yang memadai, adanya role model dan tempat berlatih.ew