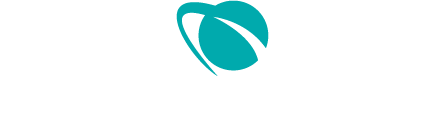Begitu namanya dipanggil, Aminah bergegas memasuki ruang periksa sambil menggendong anaknya. Hari itu, Aminah bertandang ke Puskesmas Teladan, Kecamatan Medan Kota, untuk memeriksakan batuk dan demam anaknya yang berusia 7 tahun. “Di sini murah. Kalau ke dokter, duitnya tidak cukup,” kata Aminah. Memang, Rp 35.000 ongkos berobat ke dokter sungguh berat bagi keluarga Aminah yang pas-pasan. Kalau di Puskesmas cukup Rp 1.000.
Aminah tidak sendirian. Puluhan pasien lain juga sedang antre. Memang, di saat ekonomi masih lesu, Puskesmas menjadi pelabuhan primadona masyarakat kelas bawah dalam berobat. Makanya, dalam sehari, Puskesmas Teladan tidak kurang diserbu 200 orang pasien. Padahal, Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas laboratorium itu dokternya cuma satu orang dibantu oleh 10 orang perawat, dan tenaga administrasi.
Dengan serba manual, pelayanannya masih terbilang apa adanya. Padahal, Puskesmas Teladan yang dipimpin dokter Linda Wardani Lubis itu pernah meraih penghargaan puskesmas terbaik di kota Medan. Puskesmas Teladan melayani 5 kelurahan dengan penduduk sekitar 2.500 KK (Kepala Keluarga). Bisa dibayangkan bagaimana repotnya kalau dokter Linda berhalangan ketika ada pasien yang memerlukan tindakkan medis segera. “Untunglah, selama 8 tahun bertugas di sini, saya belum pernah ketemu kejadian dramatis,” kata Linda.
Di wilayah lain, di Jalan S. Parman, Jakarta Barat, ada Rumah Sakit Jantung (RSJ) Harapan Kita. Rumah Sakit (RS) khusus penyandang sakit jantung ini sejak Februari 2001 lalu telah mengoperasikan layanan baru yang disebut jaringan telekardiologi nasional (TKN). Anda yang berpenyakit jantung, tinggal di hutan belantara atau di tengah lautan, tidak perlu repot-repot mencari RS jantung. “Di mana pun Anda berada, bisa menikmati layanan pertolongan pertama untuk pasien jantung,” kata Direktur RSJ Harapan Kita, dokter Aulia Sani, Sp.J.P., setengah berpromosi.
Tentu saja, kalau Anda memiliki alat elektrokardiograf genggam plus saluran telepon dan mempunyai akses ke pusat pelayanan EKG (elektrokardiogram) TKN. Lewat dua piranti itu, kondisi jantung seorang pasien bisa dipantau setiap saat. Dengan hanya menempelkan alat pada kulit, detak jantung pasien segera ditransmisikan ke TKN yang langsung terhubung ke unit gawat darurat RSJ Harapan Kita. Setelah merekam dalam tempo 45 detik, 2-3 menit kemudian dokter ahli jantung sudah bisa mendapatkan diagnosis dan interpretasi. Cepat, praktis dan efisien. Kejadian fatal akhirnya bisa dihindari.
Jika pasien berada di luar kota, padahal ia memerlukan tindakkan medis segera, dengan mudah pasien bisa dirujuk ke RS terdekat. Sebelum pasien sampai ke RS yang dituju, seluruh data pasien termasuk hasil pembacaan lewat EKG di RSJ Harapan Kita segera dikirim melalui faksimili/internet ke RS tujuan. Jika pasien memerlukan tindakan medis segera, bisa juga dikirim mobile intensive care yang sekaligus membawa obat-obatan.
Dua gambaran tadi memang sangat kontras. Tetapi, kekontrasan itu menegaskan satu hal: teknologi informasi (TI) sangat membantu efisiensi dan kecepatan dalam bidang kesehatan. Perkembangan TI di Indonesia yang cukup melegakan selama 5 tahun terakhir sebenarnya bisa menjadi modal untuk mempercepat adopsi dan aplikasi TI dalam dunia kesehatan. Kondisi geografis Indonesia yang bergugus-gugus pulau dan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 lalu mestinya mendorong aplikasi TI di bidang kesehatan.
Sayangnya, jalan menuju ke sana tampaknya masih berkelok-kelok. Aplikasi TI yang terintegrasi memerlukan fasilitas infrastruktur yang memadai dan tersebar merata. Bukan rahasia lagi jika infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih ada masalah. Memang banyak penyedia jasa, tapi bukan saja harganya mahal, sebarannya pun cuma terkonsentrasi di kota-kota besar. Kanal transmisi masih kecil dan kualitasnya juga banyak dikeluhkan.
Angan itu makin jauh, karena “Kesadaran pentingnya TI para pelaku kesehatan di Indonesia masih sangat minimal,” kata Dr. Muharso, bekas staf ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi Kesehatan. Data di Departemen Kesehatan (Depkes) menunjukkan, dari 1.148 RS yang ada, hanya 10 persen yang siap dengan perangkat keras. Itu pun belum terkoneksi internet. Koneksi baru ada pada RS umum pusat, RS vertikal (RSJ dan RS mata), dan RS swasta.
Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, masyarakat Indonesia sangat lemah dalam kultur membaca dan tulis-menulis. Sebaliknya, justru budaya verbal yang berkembang. Salah satu produk dari kultur ini adalah rendahnya kualitas pelaporan kerja. “Pengawasan dan pelaporan kesehatan selama ini sangat tidak memuaskan,” kata Muharso. Akibatnya, laporan itu bukan saja tidak bisa dijadikan dasar yang valid untuk menyusun informasi kesehatan, tetapi juga sangat tidak mungkin dipakai sebagai referensi untuk menelurkan kebijakan. Sebab, jika laporan salah, kebijakan turunannya pun akan salah.
Awareness pemerintah terhadap TI pun setali tiga uang. Itu tercermin dari kecilnya alokasi dana yang cuma Rp 4,2 milyar. Indonesia, kata Muharso, sebenarnya mendapat bantuan lunak Rp 39 milyar dari ADB (Asia Development Bank/Bank Pembangunan Asia) di tahun 2000. Ironisnya, hanya karena tiadanya visi yang jelas dalam pengembangan TI akhirnya bantuan itu ditolak. Rendahnya kesadaran TI juga tercermin pada kecilnya budget RS swasta yang diinvestasikan untuk pengembangan TI. RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, misalnya, dari revenue Rp 24 milyar setahun, yang dibenamkan untuk TI tak lebih dari Rp 200 juta. Berbeda dengan Singapore General Hospital (SGH). Di sana, dari revenue Rp 65 milyar setahun, sekitar 5 persennya dipakai untuk investasi dan pengembangan TI.
Sejak Mei 2000 lalu, Depkes sendiri sudah membentuk siknas (sistem informasi kesehatan nasional) yang dikelola oleh seorang kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan (pusdatin). Tujuannya untuk mengintegrasikan informasi yang selama ini dikelola masing-masing dirjen di Depkes. Menurut Bambang Hartono, Kepala Pusdatin Depkes, lembaganya sudah merumuskan “sistem pencatatan dan pelaporan data”. Tentu, tidak lagi mengacu kepada sistem pelaporan baku selama ini. Misalnya, sistem pencatatan pelayanan puskesmas terpadu dan sistem pencatatan pelayanan rumah sakit. Tetapi, model pencatatannya baru, yakni menyesuaikan kebijakan otonomi daerah. Maklum, ketika otonomi daerah, Menkes tidak lagi mendapatkan laporan rutin dari daerah (baca: “Bambang Hartono: Mulai dari Nol Lagi”).
Memang, paska otonomi daerah Januari 2001, masalah pelaporan menjadi problem rumit dan krusial. Sejak itu, Depkes yang semula bertugas menyusun kebijakan hingga implementasi di lapangan cuma menetapkan garis besar kebijakan yang bersifat umum. Implementasinya sendiri sepenuhnya didesentralisasikan ke daerah, tingkat I dan II. Berbeda dengan era sebelumnya - Depkes bisa menerima laporan dari dinas/kanwil kesehatan di daerah - di era otonomi kewajiban melaporkan itu tidak ada lagi. Aparat kesehatan di daerah bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala daerahnya.
Sebagai penanggung jawab kesehatan nasional, sudah tentu, Menkes menghadapi problem rumit karena ia tidak lagi memiliki jembatan antara penanggung jawab dan pelaksana di lapangan. Karenanya, kata Muharso, perlu diciptakan jembatan baru melalui pemanfaatan keunggulan TI. TI memang bisa menjadi jembatan Depkes dengan pelaksana dan sangat cocok dengan geografis Indonesia yang berpulau-pulau. Gambaran konkretnya kira-kira seperti SGH. Untuk mendapatkan informasi yang seragam, aksi dimulai dengan membakukan sistem informasi yang berlaku untuk semua rumah sakit (RS), baik besar maupun kecil, atau Puskesmas. Misalnya, di sebuah RS dibuat record lengkap mengenai data pasien berikut riwayat kesehatannya. Data ini disimpan di bank data. Ketika pasien tadi hendak memeriksakan kesehatannya lagi di RS lain, data record tidak perlu ditanyakan ulang karena bisa diakses dari bank data.
Selama ini, baik di Puskesmas maupun di RS, sudah ada sistem pelaporan baku. Sistem Pencatatan Pelayanan Puskesmas Terpadu, misalnya, berlaku di Puskesmas, sementara Sistem Pencatatan Pelayanan Rumah Sakit ditetapkan bagi RS. “Lewat Siknas, laporan itu akan dikelola menjadi informasi eksekutif, atau malah menjadi decision information system,” kata Muharso. Setelah melalui penapisan, kebijakan, peraturan baru, dan informasi-informasi mutakhir di bidang kesehatan akan ditebar ke daerah.
Meskipun di tingkat pusat masih nampak tertatih-tatih, sejumlah RS di daerah sudah melaju kencang. Misalnya, pengembangan LRC (learning resource center) yang dirintis oleh Pemda Jawa Tengah. LRC merupakan sistem jaringan yang terdiri atas main server dan subserver yang mudah diakses dan memiliki akses internal dan eksternal yang mampu menyediakan informasi tentang iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) kesehatan mutahir. Menurut Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kantor Wilayah Depkes Jawa Tengah, Agus Sartono, saat ini LRC masih digunakan sebagai pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan tenaga medik.
Ke depan, sistem ini direncanakan akan terkoneksi dengan LRC yang ada di sejumlah RS di Jawa Tengah, seperti RSUD Dr. Kariadi, RSUD Margono Sukarjo, dan RSUD Dr. Moewardi. Juga akan online ke Pusat Pendidikan dan Latihan Depkes, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, lembaga profesi dan dinas Depkes kabupaten, bahkan akan terhubung ke pusat LRC yang ada di seluruh Indonesia. Selain untuk bertukar informasi antar-RS, LRC juga dimaksudkan untuk memberi informasi pelayanan kesehatan pada masyarakat lewat jaringan berbasis internet.
Sebagai bagian dari program Depkes secara nasional, nantinya LRC akan memberikan informasi dan pelayanan secara lengkap. Mulai dari praktik dokter umum dan spesialis, konsultasi kesehatan, problem-problem kesehatan, perkembangan pengobatan terhadap penyakit tertentu, hingga informasi obat dan apotek. Semua itu dimaksudkan untuk memudahkan kerja sama RS dalam menangani pasien. “Karena ini masih baru, maka memerlukan persiapan yang cukup lama. Terutama penyiapan sumber daya manusianya,” kata Hartono.
Di Surabaya, RSUD Dr. Soetomo, rumah sakit rujukan untuk kawasan timur Indonesia, sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) RS sejak 1993, ketika menerima sumbangan 10 unit komputer dari ADB. Dengan berbagai modifikasi dan pengembangan, saat ini SIM-RS Dr. Soetomo yang didukung 110 unit komputer dan dioperasikan di sejumlah bagian baru bisa merekam data record pasien. Mulai dari identitas, riwayat terapi penyakit, dokter pemeriksa, biaya yang dibutuhkan, sampai informasi ruangan.
Sayangnya, program ini belum bisa dioperasikan di seluruh bagian instalasi rawat inap. Menurut Santoso Kusumo Widagdo, Kepala SIM RSUD Dr. Soetomo, kendalanya dikarenakan tidak tersedianya sumber daya. Saat ini, pengelola SIM-RS cuma 10 orang. Mereka inilah yang sekarang sedang menggenjot pelatihan di sejumlah bagian. Tidak kurang 200 orang sudah dilatih. Sayangnya, pimpinan RS kurang begitu mendukung. “Pimpinan belum meminta pelaporan menggunakan komputer, sehingga tidak bisa diterapkan dalam kerja,” kata Widagdo. Padahal, dukungan pucuk pimpinan amat penting.
SIM-RS Dr. Soetomo dibangun dengan dana APBD Jawa Timur sebesar Rp 150 juta. Cuma, instalasi rawat darurat yang begitu vital ternyata belum tersentuh TI. Pihak RS Dr. Soetomo mau membangunnya, tapi kesulitan dana. Pemda Jawa Timur pun angkat tangan. Padahal, dana yang diperlukan cuma Rp 50 juta. Tetapi, Widagdo bertekad membawa Dr. Soetomo menjadi paperless medical. Yang mengagetkan justru RS kecil seperti di Bantul SIM-RS-nya jauh lebih maju dan berkembang (baca: “Pegang Kendali RS dari Mobil”).
Sulitnya pelaku bidang kesehatan mengadopsi TI itu diamini oleh Richard Kartawijaya, CEO PT Integrasi Teknologi Tbk. Tetapi, ia tidak setuju jika divonis awareness TI para pelaku di bidang kesehatan di Tanah Air masih rendah. Richard menyodorkan bukti bahwa banyak dokter yang sudah memanfaatkan internet untuk belajar dan bertukar informasi di antara mereka. Richard tidak menampik jika pengembangan TI dunia kesehatan Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara tetangga, Singapura, misalnya. Tapi, ia yakin amat mudah untuk mengejarnya. “Kuncinya, ada kemauan atau tidak. Bila perlu, diharuskan oleh negara,” katanya.
Caranya, kata Richard, Indonesia harus mengejar dua hal. Pertama, perangkat keras, perangkat lunak maupun aplikasinya. Ini memerlukan dana yang lumayan besar. Kedua, skill dan knowledge untuk pengguna. Menurut doktor Oerip Santoso, dosen aplikasi komputer dari ITB (Institut Teknologi Bandung), Bandung, tenaga medik yang siap mengoperasikan TI bidang kesehatan sebetulnya bisa dicari dari jebolan akademi-akademi Elektromedik atau lulusan S-1 Teknik Biomedik. ITB sudah membuka pendidikan dari S-1 sampai S-3 sejak 1998/1999. “Saya kira, kita bisa mengejar dengan ketersediaan dana yang memadai,” kata Santoso. Itulah masalahnya.
Benarkah aplikasi TI di dunia kesehatan memerlukan dana besar? Untuk mendirikan TKN, seperti di RSJ Harapan Kita, misalnya, PT Telekomindo, perusahaan yang bermitra dengan RSJ Harapan Kita, harus merogoh kocek lebih dari Rp 10 miliar. Sementara, RSJ Harapan Kita bertugas menyediakan kebutuhan properti. Maklum, TKN tidak cuma dijadikan call center, tetapi juga akan dikembangkan menjadi emergency center, diagnose center, dan treatment center. Peminatnya ternyata sudah cukup lumayan: ada 1.000-an, baik dari perseorangan maupun korporasi.
Akan tetapi, bagi Elisa Lumbantoruan, President Director PT Hewlett Packard Indonesia, dana sebenarnya bukan masalah yang serius. Bahkan, dengan visi yang jelas, Depkes bisa membangun layanan ini tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Cuma, untuk menuju ke sana, perlu ada langkah-langkah yang amat mendasar. Mula-mula, membangun komunitas yang bertanggung jawab dalam sistem pelayanan kesehatan maysarakat, yaitu Depkes, RS, IDI (Ikatan Dokter Indonesia), dan farmasi. “Bahasa teknisnya, mereka perlu dibangunkan portal, atau istilah umumnya komunitas,” kata Elisa.
Pendekatannya struktural. Informasi RS, misalnya. Masing-masing RS bisa mendata kapasitas kamar inap, jadwal praktik dokter, hingga soal tarif. Demikian juga IDI, perguruan tinggi, dan akademi-akademi perawat. Lembaga-lembaga ini bisa memelopori penggunaan intranet di antara anggotanya. Setelah infrastruktur ini terbentuk, untuk mengembangkan informasi kesehatan masyarakat berbasis internet, baru melangkah ke level berikutnya, yaitu sesuatu yang bisa diakses masyarakat, seperti layanan.
Untuk itu, perlu dibangun bank data menyangkut aspek-aspek pelayanan kesehatan masyarakat. “Itu sangat mudah,” kata Elisa. Apalagi, saat ini banyak portal kesehatan yang bisa di-link. Karena kepemilikan PC (personal computer) sangat terbatas, resep sosialisasi televisi umum bisa ditiru. Dalam sebuah desa, misalnya di kantor desa, diberi sebuah PC umum yang bisa diakses lewat internet oleh semua masyarakat desa ke bank data. Kalau ini sudah terbentuk, mudah sekali mengembangkan sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih terpadu berbasiskan internet. Gagasan ini sebenarnya bida diintegrasikan dengan program Warintek Menteri Negara Riset dan Teknologi. Sayangnya, perkembangannya juga lambat.
Jika itu semua sudah terbentuk, komunitas ini menjadi amat layak untuk dikomersialkan. Perusahaan farmasi pasti tidak akan keberatan membayar karena mereka memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi RS, dokter, dan kebutuhan pasien. Dari laporan IDI, misalnya, perusahaan farmasi juga bisa melihat berita yang diperlukan masyarakat. Kalau pemerintah daerah memandang sistem informasi pelayanan kesehatan ini punya nilai, mereka pasti akan memberi kontribusi juga. “Saya kira investor akan datang sendiri, tidak perlu harus diundang,” kata Elisa. Maklum, industri healthcare merupakan industri yang tak mengenal krisis.
Lebih jauh, infrastruktur informasi ini juga bisa digunakan untuk meng-up-grade pengetahuan dokter. Sebagai bagian dari e-business, knowledge management ini bisa dikelola secara terbuka dalam sebuah database. Komunitas kesehatan bisa saling sharing dan tukar-menukar pengalaman terhadap penanganan sebuah penyakit. Untuk mengatasi minimnya tenaga ahli dokter di daerah, baik daerah terpencil maupun yang terisolir, metode telemedicine, teleconference, atau cara remote diagnosis terhadap pasien bukan mustahil dilakukan.
Kalau semua ini sudah terbangun, tak ada seorang pun yang bisa mengaturnya, termasuk pemerintah. Peran pemerintah diperlukan hanya untuk mengatur boleh-tidaknya investor asing investasi di sini. Lalu, soal perlindungan hukum terhadap masyarakat pemakai jasa. Sebab, kata Elisa, jasa di internet itu sifatnya sama saja dengan jasa kebanyakan - yang untuk memanfaatkannya diperlukan proses pengenalan dan trust. “Maka, harus ada jaminan bahwa content internet itu benar,” kata Elisa.
Sekali lagi, kalau semua ini sudah terbentuk, mengakses segala keperluan jasa kesehatan cukup dengan klak-klik dari rumah - yang saat ini masih sebatas mimpi - benar-benar sudah terwujud. Perlu informasi dokter spesialis, jam praktik, lokasi praktik, dan berapa ongkosnya, semuanya bisa diperoleh dengan sekali klik lewat internet. Tidak perlu lagi antre berjam-jam atau mondar-mandir karena tidak ada kejelasan. Mudah, murah, dan efisien.•••