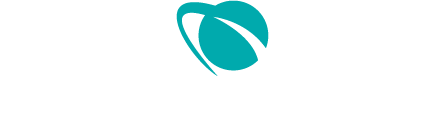Sekalipun setuju, namun Andrari mengingatkan bahwa industri software memiliki model siklus produksi berbeda dengan industri bermuatan teknologi lainnya. Industri ini membutuhkan biaya yang sangat rendah saat riset, tapi menelan biaya tinggi saat pengembangan dan kecil saat produksi. Lagi pula lifecycle-nya sangat pendek. “Jarang yang bisa melebihi dari 3 tahun,” katanya.
Menurut Marsudi, peluang untuk menumbuhkan industri ini di dalam negeri justru kian terkuak setelah krisis. Sebelum krisis, masalah pembayaran lisensi bisa jadi tidak dipersoalkan. Namun, dengan nilai tukar yang aduhai dan berlakunya hak cipta, maka package software bisa menjadi beban serius. Menurut Bobby, ada sejumlah alternatif yang bisa dilakukan, yaitu membeli produk-produk alternatif yang berlisensi murah, seperti produk India, atau beralih ke produk berbasiskan open source.
Kisworo merekomendasikan produk-produk berbasis open source. Apalagi, kini terdapat mega proyek seperti yang dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum, e-government dan Sistem Informasi Nasional. Namun, hingga kini tidak ada kebijakan pemerintah yang mengambil posisi berpihak pada produk-produk lokal. Ini berbeda dengan pemerintah Jepang dan Jerman yang tidak mau terjebak persoalan lisensi dan hukum terkait, sehingga menggariskan kebijakan ber-open source. Lagi pula tidak sedikit pihak yang meragukan kemampuan lokal turut serta dalam proyek-proyek tersebut karena persoalan kehandalannya.
Bobby melihat keputusan akhir digunakan tidaknya sebuah software ditentukan pelanggan. Pelanggan besar, seperti perbankan dan perhotelan tidak sensitif terhadap harga. Kalangan ini cenderung memilih software yang populer di kalangannya dengan kehandalan tinggi. Namun, menurut Cahyana Ahmadjayadi, Deputi Bidang Jaringan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO), produk lokal seperti MyOh hotel justru memperoleh sambutan di kalangan perhotelan nasional. Demikian juga dengan ex-office dari Bandung yang sedang naik daun di pasar lokal.
Untuk kalangan bisnis yang berskala menengah dan kecil, sensitivitas terhadap harga menjadi acuan utama. Namun, persoalan ini justru tidak terbukti bagi perusahaan-perusahaan yang pemasukannya dalam Dolar Amerika. Pada segmen pasar yang sensitif terhadap harga inilah peluang justru tersedia. Para pengembang lebih leluasa bermain di sini, apalagi memang diperlukan produk yang customized atau spesifik. Ini diakui Marsudi yang menceritakan bahwa ia dan koleganya sedang mengembangkan enterprise system untuk perusahaan skala kecil menengah. “Perusahaan yang omzetnya antara Rp.5 hingga Rp. 10 milyar,” jelasnya.
Kini, pengembangannya telah mencapai 80%. Sebelumnya, mereka berhasil melego document imaging. Namun, untuk menjualnya terpaksa dipublish di Singapura. Tentu dengan label “Made in Singapore”. Langkah serupa ternyata sudah sering dilakukan oleh lima pengembang lokal guna merebut perhatian di pasar internasional.
Untuk muncul ke permukaan, Bobby melihat begitu banyak kompetitor. Menurutnya, kini lapisan pertama seperti India, Irlandia dan Israel sudah pada tahap mapan. Lapisan kedua, seperti Polandia sedang mengarah ke sana. Sehingga peluang berkibar di arena Internasional lebih kecil. “Pemainnya jelas terus bertambah,” ujarnya.
Yang ditempuh India, menurut Marsudi, bisa jadi diterapkan dalam strategi pengembangan industri software. Pada awalnya, industri serupa di India hanya menghasilkan tenaga-tenaga murah yang direkrut perusahaan-perusahaan besar di Amerika. Lalu, berkembang menjadi industri software khusus yang bersifat tailor made. Berapa tahun lalu, industri mereka telah menghasilkan software standar dalam jumlah massal untuk keperluan pengolah kata bilingual, desktop publishing, keuangan, akunting, CAD (Computer Aided Design dan drafting program.
Selain strategi pengembangan, industri ini harus berhadapan dengan berbagai ancaman. Salah satu ancaman terbesar adalah Usage-based Software License. Konsumen bisa langsung men-download dari sumbernya. Pembayarannya dengan kartu kredit. Ancaman kedua adalah yang tersembunyi dalam bentuk regulasi berkaitan pasar bebas dan pinjaman luar negeri. Regulasi atas pasar bebas bisa mendorong produk lokal memasuki pasar ekspor. Sekalipun produk asing bisa jadi memberangus porsi lokal di pasar lokal. “Yang justru sulit untuk diutak-atik adalah yang dalam kerangka pinjaman,” ujar Andrari. Sebab kebanyakan pinjaman, terutama yang bersifat lunak dan hibah pasti memprioritaskan produk-produk negara asal pemberi pinjaman untuk sebagian besar dana yang akan dicairkan.
Ancaman yang juga tidak kalah peliknya adalah persoalan sumber daya manusia TI yang ada di Indonesia saat ini. Sekalipun diakui Markus, sejak krisis justru lebih mudah memperoleh SDM TI yang bermutu dibanding sebelumnya. Namun untuk bisa menciptakan para perekayasa software yang berkualitas Internasional jalan pajang masih terbentang di hadapan kita.•••