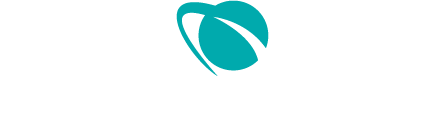Belum lama ini, dunia maya dihebohkan dengan tren Ghibli-style AI art yang menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan gambar dalam gaya legendaris Studio Ghibli. Dari foto pribadi hingga meme populer, semuanya diubah menjadi karya seni yang mirip dengan gaya Hayao Miyazaki, pendiri Studio Ghibli.
Tren inipun memicu kontroversi besar terkait hak cipta dan etika penggunaan AI. Studio Ghibli, yang dikenal karena karya animasi hand-drawn yang detail dan penuh makna, menjadi sorotan karena AI mampu "mencuri" gaya seni mereka dalam hitungan detik—sesuatu yang biasanya membutuhkan tahunan kerja keras dari para seniman.
Tidak hanya itu, CEO OpenAI, Sam Altman, juga turut memicu kontroversi ketika ia mengubah foto profilnya di platform X menjadi versi "Ghiblified" dirinya. Hal ini membuat banyak pengguna mengikuti tren tersebut, meskipun Studio Ghibli sendiri belum memberikan komentar resmi. Bahkan muncul sebuah hoax "surat peringatan hukum" yang diklaim berasal dari Studio Ghibli, menuntut penghentian penggunaan gaya mereka oleh AI. Namun, Studio Ghibli kemudian membantah keaslian surat tersebut.
Kasus ini tidak hanya menjadi fenomena viral, tetapi juga mengungkapkan pertanyaan penting: siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan oleh AI? Pertanyaan ini tidak hanya teknis, tetapi juga filosofis dan hukum, yang memerlukan analisis mendalam.
Hak Cipta dan AI: Kompleksitas yang Tak Terelakkan
Hak cipta selama ini didefinisikan sebagai perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan oleh manusia. Namun, AI mengubah paradigma ini. Menurut laporan U.S. Copyright Office (2023), karya yang dihasilkan oleh AI tanpa intervensi kreatif manusia tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, karena "keaslian manusia" adalah prasyarat utama. Keputusan ini didasarkan pada prinsip hukum yang telah berlaku selama berabad-abad, di mana pencipta karya harus memiliki kesadaran dan niat kreatif—sesuatu yang tidak dimiliki oleh mesin.
Dalam kasus Thaler v. Perlmutter (2022) di Pengadilan Federal AS menambahkan lapisan baru pada perdebatan ini. Pengadilan menyatakan bahwa AI tidak dapat dianggap sebagai "pencipta" karena tidak memiliki status hukum sebagai subjek. Keputusan ini menegaskan bahwa karya AI hanya dapat dilindungi oleh hak cipta jika ada intervensi kreatif manusia yang signifikan.
Tiga Pihak yang Terlibat: Siapa yang Punya Hak?
Dalam konteks hak cipta AI, ada tiga pihak yang saling berkaitan:
- Pembuat AI: Pembuat AI (developer) memiliki hak eksklusif atas kode program dan algoritma yang digunakan untuk menciptakan AI. Namun, hak ini tidak meluas ke karya yang dihasilkan oleh AI, kecuali ada intervensi kreatif yang signifikan. Sebagai contoh, jika pembuat AI merancang algoritma yang secara spesifik diarahkan untuk menghasilkan lukisan dalam gaya Picasso, mereka mungkin dapat mengklaim hak cipta atas karya tersebut.
- Pengguna AI: Pengguna AI adalah pihak yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan karya. Mereka mungkin memiliki hak atas karya tersebut jika mereka memberikan instruksi yang spesifik dan mengatur hasil akhir. Namun, hak ini terbatas oleh kontrak lisensi yang biasanya diberikan oleh pembuat AI. Sebagai contoh, Adobe dalam lisensi Firefly (2023) menyatakan bahwa pengguna hanya memiliki hak atas karya yang dihasilkan jika mereka memberikan input kreatif yang signifikan.
- AI itu Sendiri: AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta karya, karena hukum saat ini hanya mengakui keaslian karya yang dihasilkan oleh manusia. Meskipun AI dapat menghasilkan karya yang kompleks, hukum tidak memberikan status hukum kepada mesin sebagai subjek yang dapat memiliki hak cipta.
Prinsip Etika: Keadilan, Transparansi, dan Akuntabilitas
Dalam perdebatan hak cipta AI, prinsip etika menjadi pedoman yang tidak dapat diabaikan:
- Keadilan: Hak cipta harus dibagi secara adil antara pembuat AI, pengguna AI, dan masyarakat luas. Karya yang dihasilkan oleh AI tanpa intervensi kreatif manusia mungkin harus dianggap sebagai domain publik, seperti yang diusulkan oleh European Commission dalam AI Act (2023).
- Transparansi: Pembuat dan pengguna AI harus jujur tentang tingkat intervensi kreatif manusia dalam proses pembuatan karya. Misalnya, OpenAI mengharuskan pengguna DALL-E untuk menyertakan label "AI Generated" pada setiap karya yang dihasilkan.
- Akuntabilitas: Pembuat dan pengguna AI harus bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan oleh teknologi. Sebagai contoh, jika karya AI menyalin gaya seniman tertentu tanpa izin, pembuat AI dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta, seperti yang tercantum dalam Directive on Copyright in the Digital Single Market (Uni Eropa, 2019).
Perspektif Internasional: Bagaimana Dunia Menanggapi?
Pendekatan hukum terhadap AI dan hak cipta bervariasi di berbagai negara:
- Amerika Serikat: Hak cipta hanya diberikan kepada karya yang dihasilkan oleh manusia. Karya yang dihasilkan oleh AI tanpa intervensi kreatif manusia tidak dilindungi, seperti yang dijelaskan dalam Compendium of U.S. Copyright Office Practices (2021).
- Uni Eropa: Uni Eropa mengakui karya yang dihasilkan dengan bantuan AI, tetapi tidak memberikan hak cipta kepada AI itu sendiri. Sebaliknya, hak cipta dialokasikan kepada pengguna AI yang memberikan intervensi kreatif yang signifikan, seperti yang diatur dalam AI Act (2023).
- Jepang: Jepang mengusulkan perlindungan parsial untuk karya AI, asalkan ada bukti intervensi kreatif manusia. Contohnya, proyek AI Artist di Universitas Tokyo (2022) menghasilkan karya seni yang diakui sebagai milik pengguna AI, karena mereka memberikan instruksi yang detail.
- Tiongkok: Tiongkok memiliki pendekatan yang lebih fleksibel. Pengadilan di Beijing (2021) memutuskan bahwa karya yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi oleh hak cipta jika ada "partisipasi kreatif manusia yang signifikan".
Pada Akhirnya Harus Mencari Keseimbangan yang Adil
Hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI masih menjadi perdebatan yang belum terselesaikan. Namun, dengan mempertimbangkan prinsip etika seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta memahami kerangka hukum yang ada di berbagai negara, kita dapat menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak.
Menurut Harvard Law Review (2023), solusi yang mungkin adalah mengakui karya AI sebagai "karya bersama" antara manusia dan mesin, di mana hak cipta dialokasikan kepada pihak yang memberikan kontribusi kreatif yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan, tetapi juga mendorong inovasi teknologi tanpa mengabaikan hak-hak kreatif manusia.
Dalam era di mana AI semakin mempengaruhi kehidupan kita, penting untuk terus memperbarui kerangka hukum dan etika agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa teknologi AI tidak hanya menjadi alat, tetapi juga mitra yang bertanggung jawab dalam penciptaan karya kreatif.•••